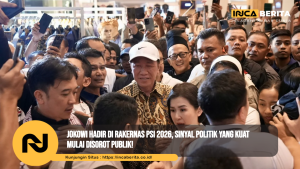Quiet Quitting: Fenomena Diam-Diam Resign Tanpa Terlihat
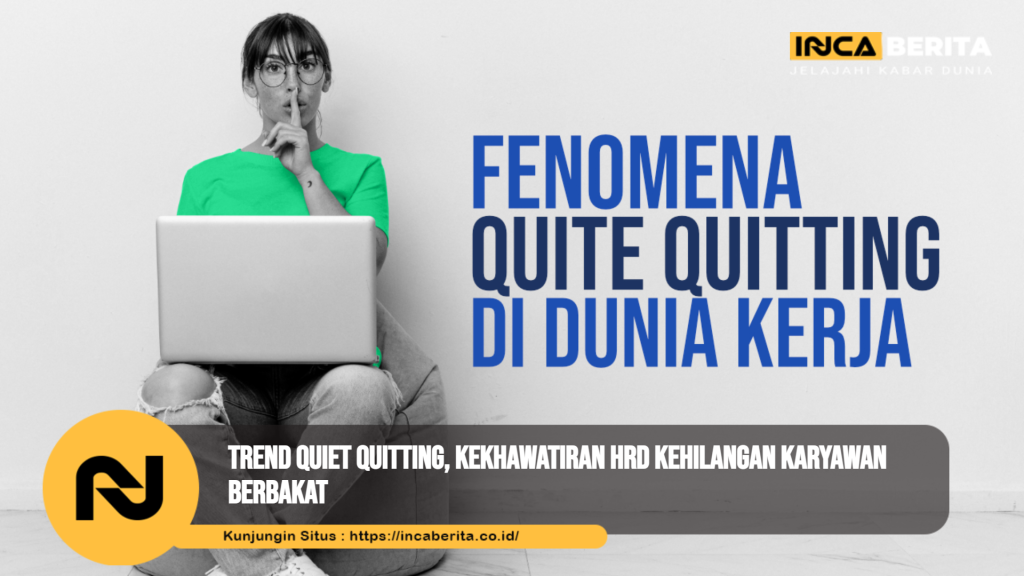
Jakarta, incaberita.co.id – Mungkin kamu pernah mengalami momen seperti ini: tugas sudah selesai, tapi kamu diminta bantu meeting divisi lain. Atau, kamu tetap ditagih update proyek di akhir pekan lewat WhatsApp. Dan lama-lama kamu merasa lelah. Lelah secara fisik, lelah secara emosional, bahkan secara nilai.
Lalu kamu memutuskan: “Udah, gue kerja sesuai jobdesk aja deh. No more, no less.”
Selamat datang di tren yang dinamakan quiet quitting.
Quiet quitting bukan resign beneran. Bukan juga mutung, lalu menghilang tanpa pamit. Quiet quitting adalah bentuk “stay but disengaged”—tetap bekerja, tapi hanya sebatas tanggung jawab formal. Tidak ambil lebih, tidak inisiatif ekstra, tidak ikut lembur kalau bukan kewajiban.
Konsep ini mendadak viral di media sosial, terutama di TikTok dan Twitter. Banyak Gen Z yang mengaku mulai quiet quitting karena merasa burnout, tak dihargai, atau karena sadar bahwa “loyalitas buta” ke perusahaan bukan jaminan kesejahteraan.
Fenomena ini semakin terasa setelah pandemi. Work from home membuka kesadaran baru bahwa hidup bukan cuma kerja. Banyak orang akhirnya mempertanyakan ulang: apakah jam kerja yang fleksibel harus diisi dengan kerja nonstop? Apakah lembur tanpa bayaran itu bentuk dedikasi atau eksploitasi?
Yang menarik, quiet quitting tidak hanya terjadi di sektor kreatif atau startup. Di birokrasi, perbankan, bahkan korporasi mapan pun fenomena ini mulai muncul diam-diam. Seorang karyawan di bagian IT BUMN pernah berkata, “Gue kerja sesuai KPI, tapi nggak bakal ikut acara nginep kantor atau bikin project tambahan lagi. Capek batin.”
Jadi, meski istilahnya “quiet”, implikasinya cukup berisik. Karena ketika banyak karyawan memilih menahan kontribusi, produktivitas dan kultur kerja bisa terguncang.
Mengapa Quiet Quitting Terjadi? Bukan Malas, Tapi Ada Luka yang Tak Terlihat

Image Source: Yesdok
Ada anggapan bahwa karyawan yang quiet quitting adalah generasi manja, tidak tahan tekanan, atau tak punya ambisi. Tapi benarkah sesederhana itu?
Menurut laporan riset dari Gallup, engagement karyawan global menurun signifikan sejak 2021. Banyak karyawan merasa tidak terlibat emosional dalam pekerjaan mereka. Dan ketika engagement rendah, quiet quitting bukanlah pilihan, tapi mekanisme bertahan.
Beberapa penyebab utama quiet quitting antara lain:
1. Burnout Berkepanjangan
Selama pandemi, batas antara kerja dan kehidupan pribadi makin kabur. Zoom meeting bisa sampai malam, grup kerja aktif sampai subuh. Semua itu menguras energi, dan pada akhirnya membuat banyak karyawan kehilangan semangat.
2. Tidak Diapresiasi
Karyawan yang merasa kontribusinya tak dihargai—baik secara finansial maupun moral—cenderung menarik diri. Banyak yang sudah bantu di luar jam kerja, ikut proyek tambahan, tapi tak ada peningkatan gaji atau sekadar ucapan terima kasih.
3. Ekspektasi yang Tidak Realistis
Beberapa perusahaan punya budaya hustle yang terlalu keras. Kerja cepat dianggap bukti loyalitas. Tidak ikut lembur bisa dicap “tidak punya inisiatif”. Hal ini menekan karyawan untuk terus memberi lebih tanpa batas.
4. Kurangnya Tujuan dan Visi Jelas
Karyawan yang tidak tahu kenapa mereka mengerjakan sesuatu, atau apa dampaknya, akan kehilangan motivasi. Ketika pekerjaan terasa seperti mesin tanpa makna, semangat pun menurun.
5. Keseimbangan Hidup yang Terancam
Karyawan masa kini, khususnya Gen Z dan milenial, punya nilai hidup yang lebih seimbang. Mereka ingin bisa menikmati waktu untuk keluarga, hobi, dan diri sendiri. Jika kerja mulai merampas itu, maka quiet quitting menjadi pilihan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa quiet quitting bukan karena malas. Tapi karena terlalu lama merasa diperlakukan seperti mesin, bukan manusia. Dan inilah bentuk perlawanan yang paling sunyi.
Dampak Quiet Quitting Bagi Perusahaan dan Dunia Kerja
Kebayang nggak, kalau satu tim diisi oleh lima orang yang semuanya memutuskan untuk quiet quitting? Mereka tetap kerja, tetap datang, tetap isi absensi. Tapi tak satu pun yang inisiatif atau ambil langkah lebih. Hasilnya: tim stagnan. Kreativitas mandek. Target pun tersendat.
Meski tidak selalu buruk, quiet quitting punya dampak serius jika terjadi secara kolektif. Berikut beberapa efek yang mulai dirasakan banyak perusahaan:
1. Menurunnya Produktivitas Tim
Karyawan yang hanya kerja sesuai standar minimum tidak akan memberi kontribusi strategis. Mereka hanya menjalankan perintah, tanpa berpikir dua langkah ke depan.
2. Atmosfer Kerja Jadi Datar
Tim yang penuh dengan quiet quitter biasanya kehilangan semangat kolaborasi. Tak ada lagi diskusi mendalam, tak ada yang peduli dengan visi besar, dan hubungan antar anggota cenderung transaksional.
3. Pemimpin Jadi Frustrasi
Manajer yang punya target besar akan merasa frustrasi jika timnya tidak responsif. Apalagi kalau harus “menghidupkan” orang-orang yang sudah tak tertarik untuk ikut berkontribusi ekstra.
4. Retensi Talenta Top Menurun
Karyawan berprestasi yang melihat lingkungan kerja pasif cenderung pindah. Mereka mencari tempat yang lebih hidup, lebih menghargai kontribusi, dan punya kultur inovatif.
5. Tantangan dalam Inovasi
Quiet quitting mengurangi potensi lahirnya ide-ide baru. Karena inovasi lahir dari orang-orang yang berpikir lebih dari jobdesk—yang bersedia melampaui ekspektasi.
Namun, perlu digarisbawahi: quiet quitting tidak selalu salah. Dalam beberapa konteks, justru bisa jadi tanda bahwa batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan perlu ditegaskan. Tantangannya adalah bagaimana perusahaan bisa membaca sinyal ini sebelum semuanya telanjur apatis.
Cara Menghadapi Quiet Quitting – Perspektif Karyawan dan Manajemen
Menanggapi quiet quitting tidak cukup dengan menyuruh karyawan “semangat dong” atau “jangan terlalu perhitungan”.
Perusahaan perlu pendekatan yang lebih dalam, dan karyawan pun bisa punya cara yang lebih sehat untuk bertahan.
Bagi Manajemen:
1. Dengarkan Lebih Banyak, Perintah Lebih Sedikit
Karyawan butuh merasa didengar. Sesi feedback dua arah, diskusi tanpa tekanan, dan ruang untuk menyampaikan keresahan bisa membuka jalan.
2. Evaluasi Beban Kerja dan Ekspektasi
Periksa apakah tugas-tugas tambahan sudah terlalu banyak? Apakah lembur menjadi norma? Jika ya, mungkin sistem perlu diubah.
3. Tunjukkan Apresiasi secara Nyata
Bukan hanya lewat plakat, tapi lewat bonus, promosi, atau peningkatan kualitas kerja. Karyawan akan lebih hidup jika tahu bahwa kerja kerasnya dihargai.
4. Fokus pada Tujuan, Bukan Hanya Jam Kerja
Alih-alih memantau berapa jam karyawan duduk di depan laptop, ukur kontribusi nyata mereka terhadap tujuan tim.
5. Ciptakan Lingkungan Kerja yang Sehat
Budaya kerja yang terlalu kompetitif, penuh tekanan, atau penuh drama bisa mempercepat munculnya disengagement. Fokuslah pada kolaborasi dan psychological safety.
Bagi Karyawan:
1. Kenali Batas Dirimu Sendiri
Kalau kamu merasa burnout, jangan langsung quiet quitting. Evaluasi dulu: apa yang membuatmu lelah? Apakah ini soal beban, atasan, atau karena kamu tidak cocok dengan peran?
2. Komunikasikan Ketidaknyamanan
Daripada diam dan menarik diri, lebih baik sampaikan pada atasan. Beberapa pemimpin tidak sadar ada yang salah sampai kamu bicara.
3. Bangun Rutinitas yang Menyehatkan
Work-life balance bukan hanya soal jam kerja, tapi soal bagaimana kamu mengisi waktu luang. Cari hobi, olahraga, tidur cukup, dan jangan bawa kerja ke ranjang tidur.
4. Cari Komunitas yang Mendukung
Berada dalam tim atau lingkungan kerja yang suportif bisa menjaga semangatmu. Kalau tidak ada di kantor, cari di luar.
5. Pertimbangkan Ulang Tujuan Kariermu
Jika kamu merasa stagnan, mungkin ini waktunya mengubah arah. Quiet quitting bisa jadi sinyal bahwa kamu butuh tantangan baru.
Apakah Quiet Quitting Akan Bertahan atau Justru Menjadi Gerbang Revolusi Dunia Kerja?
Quiet quitting, pada akhirnya, adalah gejala dari ketidakseimbangan. Ia lahir dari kelelahan kolektif dan budaya kerja yang terlalu menuntut tanpa memberi cukup.
Tapi bisa jadi, justru lewat fenomena ini, kita dipaksa untuk mendesain ulang cara kita bekerja.
Mungkin ini momen kita untuk:
-
Menghargai pekerjaan sebagai bagian dari hidup, bukan seluruh hidup
-
Membangun organisasi yang berfokus pada manusia, bukan sekadar target
-
Menghapus glorifikasi hustle culture yang melelahkan dan tidak berkelanjutan
-
Menyadari bahwa loyalitas tidak bisa dituntut, tapi dibangun
Apakah quiet quitting akan hilang? Mungkin tidak. Tapi ia akan berevolusi. Bisa jadi menjadi bentuk career downshifting, job crafting, atau bahkan resignation in silence.
Dan semua itu bukan tanda kemalasan—tapi tanda bahwa orang-orang ingin hidup secara utuh.
Penutup: Saatnya Mendengarkan Sunyi yang Bersuara
Quiet quitting bukan sekadar tren. Ia adalah cermin. Cermin bagi perusahaan untuk melihat bagaimana mereka memperlakukan orang. Dan cermin bagi karyawan untuk melihat apakah mereka masih hidup dalam pekerjaan mereka.
Di era yang serba cepat dan penuh tekanan, barangkali kita semua butuh mengingat satu hal:
Kerja keras itu baik. Tapi hidup dengan utuh—itu lebih baik.
Baca Juga Konten Dengan Artikel Terkait Tentang: Lokal
Baca Juga Artikel Dari: Warganet Ramai Memposting dan Mengibarkan Bendera One Piece Menjelang HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025, Ada Apa?